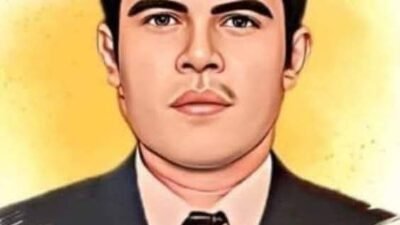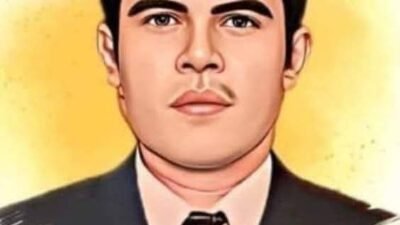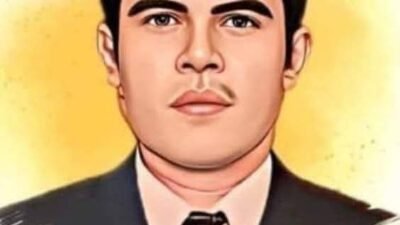Oleh : Yusra Wafilma
Pemred : Wartapatroli com
Dunia pers, yang dahulu berdiri tegak sebagai pilar keempat demokrasi, kini kadang tampak seperti panggung komedi gelap. Di atas panggung itu, sejumlah “wartawan” (Baca – Oknum) muncul membawa KTA yang dicetak sekelas bros undangan pesta pernikahan, lalu berdiri dengan penuh percaya diri seolah mereka pewaris tunggal kebenaran.
Mereka datang ke acara resmi bukan dengan pena yang haus akan fakta,
melainkan dengan kantong yang lapar akan amplop.
Sebuah investigasi kecil yang penulis lakukan di banyak kegiatan memperlihatkan pola yang mirip irama, klasik
datang terlambat, duduk paling dekat dengan meja konsumsi,
bertanya paling sedikit,
tapi paling duluan saat antre nasi kotak.
Saat panitia sibuk mempersiapkan acara, mereka sibuk mempersiapkan kalimat
“Transport-nya belum, Kalau tidak ada, nanti beritanya… ya, begitulah.”
Nada ancaman sehalus embun, namun menusuk seperti jarum karat.
Di tengah suasana itu, kita seakan menyaksikan teater absurd.
Betapa janggalnya profesi mulia ini direduksi menjadi ritual meminta-minta dengan KTA sebagai tongkat ajaib. Seakan kartu itu bukan identitas kerja, melainkan password untuk membuka kotak amal.
Jika ini adalah liputan investigatif, maka temuan awalnya menyedihkan
Banyak di antara mereka tidak mengenal lead, tidak mengerti angle, dan tidak pernah tahu bahwa berita memiliki struktur. Mereka hanya tahu satu hal struktur amplop yang diisi tipis-tipis.
Dalam catatan lapangan, yang sering penulis dengar perangkat daerah dan panitia kegiatan pun dibuat resah.
Ada yang sampai memeriksa ulang undangan, memastikan apakah mereka sedang mengundang jurnalis sungguhan atau justru mengundang “rombongan duta amplop”.
Ironisnya, di balik semua itu ada sebuah irama puitis yang tak diinginkan
profesi yang seharusnya berdiri tegak kini membungkuk,
bukan karena beban fakta,
melainkan karena menengadahkan tangan demi recehan yang bahkan tak layak disebut biaya tinta.
Ketika KTA Menjadi Tongkat Sihir
Seakan ada mantra yang beredar
“Tempelkan KTA, maka semua pintu terbuka.”
Pintu konferensi pers, pintu konsumsi, pintu uang rokok.
Padahal bila diperiksa, KTA itu sering hanya berfungsi sebagai dekorasi dada yang tak berbeda dengan gantungan kunci souvenir yang dijual di pasar malam.
Organisasi pers yang kredibel pun kewalahan.
Mereka seperti penjaga perpustakaan tua yang terpaksa mengingatkan bahwa buku-buku itu seharusnya dibaca bukan dijadikan tatakan gelas.
Puitika Profesi yang Terluka
Di tengah hiruk-pikuk informasi, publik sebenarnya semakin jeli.
Mereka bisa membedakan mana jurnalis yang menulis dengan cahaya,
dan mana yang mendekati dengan bayangan.
Sementara wartawan sungguhan menempuh perjalanan panjang meliput data bencana dalam hujan, dengan retorika parodi banjir bandang dan longsor mencatat dalam ribut angin,
menyimpan suara narasumber dalam rekaman panjang
oknum berkamera ponsel malah hanya menunggu momen bagi-bagi konsumsi,
seperti burung pipit yang hanya datang ketika ada remah roti.
Pada titik ini, profesi seakan berada dalam sebuah elegi,
sebuah nyanyian sedih tentang kehormatan yang karib diringkus oleh segelintir orang bersaku kosong namun bermuka tebal.
Kesimpulan Wartawan abal-abal bukan hanya mencoreng profesi.
Mereka adalah kabut pekat yang menyesatkan arah,
mengubah ruang publikasi menjadi arena pungutan liar,
dan membuat jurnalisme kehilangan sebagian keindahan esensialnya.
Kita harus mengingatkan mereka, dengan satire maupun tegas
profesionalisme tidak bisa dicetak di kartu plastik.
Integritas tidak lahir dari amplop.
Dan KTA bagai manapun bentuknya
bukan tiket resmi untuk mengemis atas nama pers.(*)